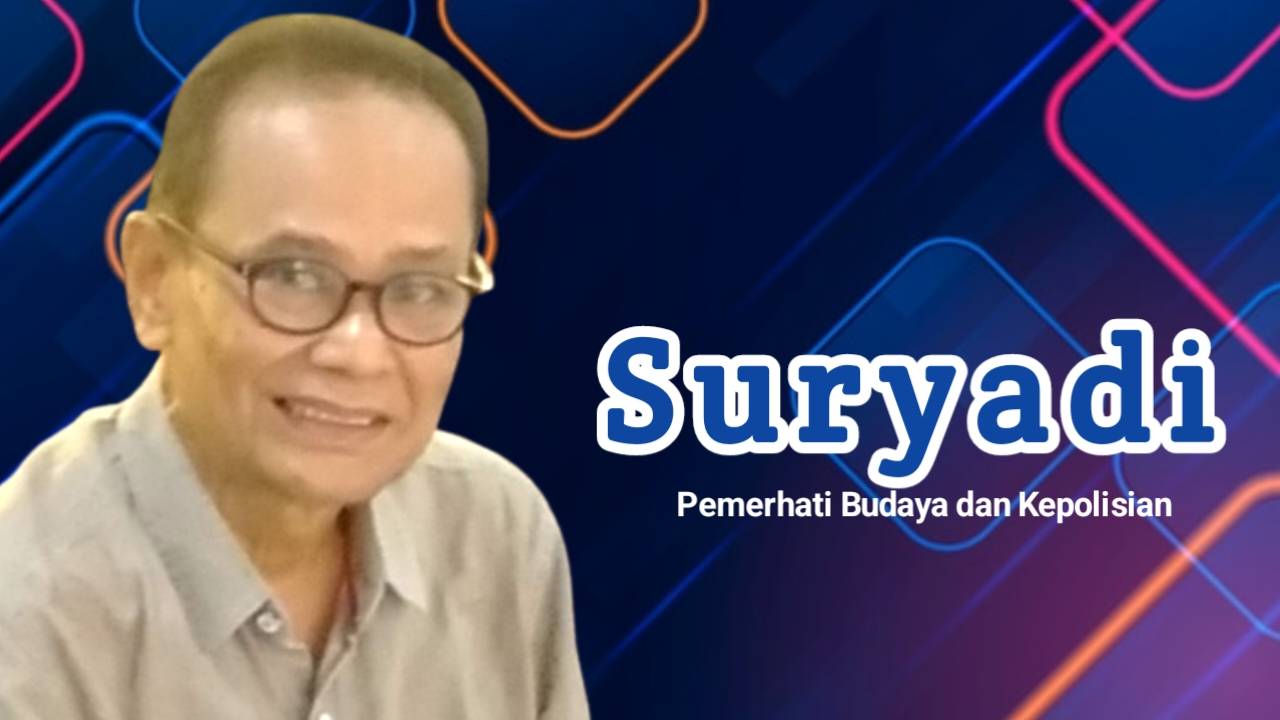Jujur, Hipokrit, dan Manusia Indonesia
 Suryadi
Suryadi, telisik indonesia
Minggu, 20 April 2025
0 dilihat

Suryadi, Pemerhati Budaya & Kepolisian. Foto: Ist.
" Kita semua mengutuk korupsi atau istilah barunya 'komersialisasi jabatan', tetapi kita terus saja melakukan korupsi dan dari hari ke hari korupsi bertambah besar saja "

Oleh: Suryadi
Pemerhati Budaya & Kepolisian
JUJUR itu sebuah nilai. Sampai kapan pun, andai bentuk dan warnanya berubah, jujur tetaplah satu nilai. Tak tergoyahkan! “Jujur merupakan nilai moral,” tulis Haryatmoko, yang sejak 2015 juga mengajar Program Doktor di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) (“Prinsip Prinsip Etika”, 2024: 19).
Budayawan Mochtar Lubis semasa hidupnya, dalam pidato kebudayaan yang begitu bersejarah di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, jelang 32 tahun setelah Indonesia merdeka 6 April 1977, menempatkan “Munafik” atau “Hiprokrit” pada deret pertama sifat atau ciri utama manusia Indonesia. "Kita semua mengutuk korupsi atau istilah barunya 'komersialisasi jabatan', tetapi kita terus saja melakukan korupsi dan dari hari ke hari korupsi bertambah besar saja.
Sikap manusia Indonesia yang seperti ini yang memungkinkan korupsi begitu hebat .... ("Manusia Indonesia", 2017: 19). Tulisan ini tidak ingin menggeneralisasi bahwa semua manusia Indonesia koruptor, tetapi Jakob Oetama dalam pengantarnya untuk “Manusia Indonesia” menulis. “Stereotip tidak seluruhnya benar, tidak pula seluruhnya salah.
Stereotip tumbuh dalam benak orang karena pengalaman, observasi, tetapi juga oleh prasangka dan generalisasi. Tetapi saya berpendapat, stereotip bermanfaat sebagai pangkal tolak serta bahan pemikiran serta penilaian secara kritis, maka relevanlah (2017: vii).
ORGAIZED Crime and Corruption Reporting (OCCRP) memasukan nama Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi), dalam daftar nominasi finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan terkorup 2024.
Belakangan (3/1/2024) OCRP memberikan klarifikasi, bunyinya antara lain, tak ada bukti Jokowi terlibat dalam tindakan korupsi yang menguntungkan pribadi sepanjang menjadi Presiden. Jokowi bersama sejumlah pemimpin negara lainnya yang terpilih sebagai finalis tokoh terkorup, adalah berasal dari nominasi publik yang mendapatkan dukungan daring terbanyak secara global. “Karenanya, dianggap beralasan untuk diikutsertakan. OCCRP tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, karena saran datang dari orang-orang seluruh dunia. Salah satunya OCCRP memasukkan nama Joko Widodo sebagai tokoh terkorup karena banyak menerima kiriman surat elektronik (surel) (hukumonline.com).
Jika demikian, maka dapat dimaknai “kejadiannya yang menimpa Jokowi itu, secara hukum tidak beralasan, dan masih terbuka kesempatan untuk membuktikan benar atau salah”. Lantas, sesuai locos delicti-nya, Pengadilan mana yang akan mengadili perkara ini? Tentu, pertanyaan ini terlalu bodoh. Di negeri yang konon “tajam ke bawah tumpul ke atas ini”, agar tak liar tetap berlaku pengaduan ada persyaratannya, “Siapa pengadu yang memenuhi syarat atau tidak untuk ditindaklanjuti.”
Meskipun demikian, korupsi yang melibatkan penguasa, pengusaha, bahkan jika korupsi juga dapat dikatakan “sebagai perbuatan kriminal menguasai tanpa hak dan merugikan orang banyak”, dapat dikatakan di negeri ini sudah berlangsung sejak lama. Mochtar Lubis dalam pidato kebudayaannya di TIM seperti di awal pembuka tadi, melanjutkan, “…korupsi begitu hebat berlangsung terus-menerus selama belasan tahun di Pertamina (BUMN, pen), umpamanya, meskipun fakta-fakta sudah jelas dan terang, hingga hari ini belum ada tindakan hukum diambil terhadap para pelaku utamanya” (2017: 19).
Dengan demikian pula, dapat dikatakan, “vonis” OCCRP itu bak “pepesan kosong”, sepertihalnya omong-omong besar dari pemimpin ke pemimpin pada eranya di negeri ini, yang selalu bicara “Akan berada paling depan memimppin pemberantasan korupsi”, “Berantas habis koprupsi”, atau “Tidak ada tempat bagi korupsi”. Jadi, tak seperti pemimpin sebuah negeri yang diramaikan lewat media sosial, menyediakan 100 peti mati dan satu di antara untuk dirinya sendiri.
Baca Juga: Museum dan Nilai-Nilai Juang
Bukan tak ada penindakan terhadap pelaku dan kejahatan korupsi di negeri ini. Tetapi adalah kenyataan, setiap kali ada peringatan atau bahkan tindakan nyata, bermunculan pula kejahatan korupsi baru. Mungkin, tak berlebihan jika dikutip kembali pidato Mochtar, “…kita semua mengutuk korupsi atau istilah barunya 'komersialisasi jabatan', tetapi kita terus saja melakukan korupsi”.
Boleh jadi, “kita” yang dimaksudkan Mochtar adalah bentuk kekhawatiran melihat manusia Indonesia dari waktu ke waktu hingga kini, sehingga seperti “tinggal tunggu kesempatan saja”. Jakob pun mengajak, “…saya berpendapat, stereotip bermanfaat sebagai pangkal tolak serta bahan pemikiran serta penilaian secara kritis, maka relevanlah.”
Melilit
MUNGKIN tak berlebihan, seperti bertebaran di banyak media di negeri ini, jika korupsi atau kejahatan yang bertujuan memperkaya diri sendiri dengan merugikan orang banyak, bertumbuh bernas dan segar di negeri ini. Seperti melilit dan menyambar kemana-mana.
Tiap kali ditindak, tiap kali ada peringatan, tiap kali ada khotbah, selalu dijawab oleh kemunculan “maling-maling” bernama keren “koruptor” di antero negeri. Kali ini pengu asa, kemudian susul menyusul pengusaha atau aparat penegak hukum tabaok rendong (Minang: terbawa serta alias “berjamaah”).
Lain waktu tinggal sebut, ada pereman; mereka yang mengaku anggota Organisasi Massa (Ormas); atau sekadar mencari keuntungan di tengah sempitnya jalan dengan mengatur lalu-lintas seraya siap-siap marah bila tak diberi fulus. Semua patut diduga dibiarkan hidup atau mungkin sudah puluhan tahun tanpa kepedulian pekerti. Lantas, ramai-ramai berkata moralis, “Begitulah kalau pendidikan pekerti dihilangkan dari sekolah.”
Baru-baru ini media memberitakan, seorang hakim dan “rombongannya” terlibat suap atas perkara yang telah ia vonis. Tak lama kemudian, menyambar kemana-mana, termasuk ke panitera, pengacara pembela pihak yang berperkara, dan tentu saja yang terlibat perkara.
Masih kental berbalut duit, belum lama ini terdengar pula tiga aparat penegak hukum (APH) tewas oleh dua aparat bersenjata di arena sabung ayam. Sungguh bikin geleng-geleng kepala. Bukan main! Pasti sudah menahun alias bukan kali itu saja judi sabung ayam tersebut berlangsung. Atas kejadian ini, sudah seharusnya membuat APH di daerah lain, waspada mungkin saja judi sabung ayam serupa juga sudah ada di daerahnya.
Tak masuk akal sehat, ada pula seorang perwira menengah yang pimpinan instansi Polri di tingkat kabupaten, terlibat kejahatan seksusal terhadap anak di bawah umur. Kalau si pimpinan itu punya kelainan, maka patut diduga, sekurangnya potensi itu baru termunculkan kali ini. Tapi, koreksi lebih dalam, tentu perlu dilakukan pada proses penerimaan dan selama pendidikan. Setidaknya, patut dipertanyakan, bagaimana masa lalu sejak kecil hingga kini seorang yang lulusan Akademi Kepolisian (Akpol).
Sebelum hakim dan “rombongannya” yang ditangkap APH setelah terima puluhan milyaran rupiah dari yang berperkara melalui pengacara, terungkap lebih dulu korupsi di sebuah BUMN. Mirip-mirip yang ditudingkan Mochtar. Selain oplos minyak --yang logikanya Negara rugi--, juga terkait dengan uang triliunan rupiah yang diterima direksi, meski mereka setiap bulan sudah bergaji puluhan miliar rupiah. Mungkin rakus ya!
Tak luput pula keluhan pengusaha retail yang merasa “tidak aman dan tidak nyaman” karena kerap dimintai duit oleh sejumlah pereman yang mengaku-ngaku anggota Ormas. Gubernur baru Jabar, Dedy Mulyadi, baru-baru ini turut melontarkan hal serupa, tapi ia enggan meladeni ajakan “duel debat” tentang kebenaran pemalakan ini dari sebuah Ormas.
Ada pula yang dari tahun ke tahun kerjanya tunggu warga yang mau renovasi rumah di suatu kawasan perumahan, Bila datang matrial bangunan, mereka mencegat dan memintai duit kepada si tukang yang merenovasi. Bahkan, mereka yang akan melakukan perbaikan listrik PLN di suatu perumahan, juga dicegat dimintai duit.
Di atas tadi hanya beberapa saja. Tetapi, melihat ragam mereka yang sengaja melibatkan diri, sungguh mengurut dada. Mulai dari yang kecilan-kecilan, pengusaha, pejabat, pengacara, aparat, dan APH seperti polisi dan hakim. Jumlah ini akan membesar lagi jika dimasukkan sejumlah pejabat, apakah itu kepala daerah, Menteri, politisi yang anggota Parlemen (daerah dan RI) atau bukan, petugas yang berhubungan langsung dengan perkara, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pendek kata tinggal tangguk, beragam profesi terkena. Yang meciduk, benarkah tinggal tunggu kesempatan saja?
Soal angka-angka berapa kerugian negara, ada yang menyoal korupsi itu merugikan keuangan Negara. Jadi, silakan saja hitung. Ada yang berwenang menghitungnya, berapa besar rupiah atau dolar langsung atau persentase saja terhadap anggaran negara dan daerah (APBN/APBD).
Etikanya, ya tak Bertetika
DALAM sebuah tulisan berjudul “Apa Harga dari Sebuah Pelanggaran Etika? (Medium.com, Mart 20, 2025) yang bergaya bercerita yang dikirimkan kepada penulis, seorang mahasiswa pascasarjana UNMalang, Jatim, Imanuela Putri, seolah ingin menulis, “Kini masanya tak beretika itulah etika”. Ngeri juga ya!
Baca Juga: Ada Apa di Balik #KaburAjaDulu?
Terbayangkan di benak penulis ketika hukum atau aturan --di bidang apa pun-- berjalan tanpa etika, sekaligus bukan kristalisasi dari kekuatan moral masyarakat, apa jadinya ya? Atau, sebaliknya, aturan ditelurkan hanya lunas oleh jawaban, “Bukankah UU yang sudah disetujui itu, RUU-nya sudah lama dibahas di Parlemen”. Bukankah, antara lain politisi punya kewajiban mendidiknya sampai bermoral, bukan malah dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi atau sekadar mengatasnamakan kelompok.
Padahal, di lain piha diketahui, mayoritas kursi di Parlemen, terdiri atas partai-partai koalisi Pemerintah. Tambahan lagi, pembahasan konon jauh dari terbuka luas kepada publik. Terbuka itu, antara lain, berarti “masyarakat ikut bertanggungjawab atas lahirnya suatu aturan”. Bukan bertanggungjawab cuma setelah aturan diundangkan.
Ketidaksempurnaan manusia tidak bisa jadi pembenaran atas dasar “coba-coba siapa tahu lolos”. Korupsi, tak lain adalah tindakan “lebih canggih daripada sekadar maling” dari sejumlah orang pintar (bukan cerdas dan luhur), meski sama-sama mengangkangi hak orang lain secara tanpa hak.
Maka, dapat dipastikan, setiap “maling” atau koruptor, bukan cuma pelawan hukum, tapi juga tak beretika dan tak bermoral. Pesohor yang hidup di masa lalu, Loc Acton (1833 – 1902), pernah mengingatkan, “Kekuasaan itu cenderung korup, Kekuasaan korup seratus persen”.
Bahkan, jika agama betul-betul menjadi pegangan (bukankah setiap WNI harus beragama?) maka beragama itu adalah berhikmah dengan baik. Manusia selalu diingatkan untuk selalu waspada terhadap kekuasaan. Sebab, ujian terberat adalah kekuasaan. Dapat dibayanghkan, ketika korupsi atau maling itu tak sekadar duitnya, tapi mulai dari sumbernya, maka betapa banyak manusia yang terdampak. Korupsi mulai dari kebijakan!
Ambil contoh sederhana, ketika seorang Menteri korupsi bantuan sosial (bansos). Bayangkan betapa banyak mereka yang sudah miskin menjadi bertambah miskin kualitas hidupnya. Demikian pula, dalam skala kecil bila seorang Ketua Rukun Tetangga (RT) cuma peduli menguntungkan diri sendiri, semisal ganti rugi lahan yang pasti memberinya komisi karena ia merangkap sebagai calo (perantara), bagaimana nasib masyarakat miskin yang butuh perbaikan kehidupan berekonomi di lingkungannya?
Norma, tulis Haryatnmoko, menghubungkan nilai dengan tindakan nyata sehingga norma bisa menjadi sarana untuk mencapai tujuan. Sedangkan tujuan selalu terkait dengan suatu nilai. Nilai yang dijunjung tinggi akan disertai norma, dan pelanggaran terhadapnya akan mendapat sanksi (2017: 13). Tinggal sanksinya berupa hukuman atau sanksi sosial atau kedua-duanya.
Bukankah sanksi berupa hukuman badan, kini sudah terbukti tidak mempan menjerakan? Kejujuran itu Nilai. Perlu pendidikan dan pembiasaan agar berbudaya. Para orangtua di masa lalu, setiap kali ada perbuatan buruk, jangankan yang tergolong kriminal, mereka selalu berkata, “Itulah kalau orang tak berbudaya.” Perlu kepedulian nyata dari setiap orang terhadap lingkungannya. Lingkungan apa saja! (*)
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS