Mendiskusikan Kembali Pemilu Serentak
 Efriza
Efriza, telisik indonesia
Minggu, 24 Januari 2021
0 dilihat

Efriza, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP). Foto: Ist.
" Maksud dari coattail effect adalah partai-partai politik yang dipilih dalam Pilpres cenderung dipilih pula dalam Pemilu Legislatif karena diserentakkan. "

Oleh: Efriza
Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP)
SAAT ini, DPR kembali merumuskan ulang mekanisme Pemilu. Pemilu Serentak April 2019 lalu, dianggap rumit berimbas banyaknya anggota penyelenggara pemilu ad-hoc yang meninggal dunia. Padahal, Pemilu Serentak kala itu dianggap pemilu yang sesuai dengan sistem presidensial.
Skema yang dilakukan selama ini dianggap tak selaras antara sistem pemilu dengan sistem pemerintahan. Misalnya, memisahkan Pilpres dengan Pemilu Legislatif, serta mendahulukan pemilu legislatif, merupakan bentuk anomali.
Dikatakan anomali, karena sistem presidensial memisahkan antara parlemen dan kepresidenan. Kedua institusi memiliki legitimasi berbeda dan tak saling ketergantungan di antara keduanya.
Sayangnya, Mahkamah Konstitusi turut memutuskan mengenai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 25 suara nasional atau 20 persen kursi DPR, tetap diberlakukan. Upaya efektivitas sistem presidensial dengan mekanisme pemilu serentak, tak lagi bermakna kecuali terjadinya coattail effect (efek ‘ekor jas’), meski tak maksimal.
Maksud dari coattail effect adalah partai-partai politik yang dipilih dalam Pilpres cenderung dipilih pula dalam Pemilu Legislatif karena diserentakkan.
Perdebatan ini mengemuka di Gedung Senayan, dalam upaya merumuskan kembali mekanisme pemilu. Perdebatan tidak saja ingin merumuskan kembali mekanisme pemilu serentak yang lebih baik, tetapi turut pula menyinggung menihilkan presidential threshold atau tetap mempertahankannya. Tulisan ini ingin mendiskusi evaluasi atas penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 lalu.
Pilihan Menyerentakkan Pemilu
Pemilu Serentak pada tahun 2019 lalu, acap disindir dengan Pemilu Borongan 5 Kotak. Maksud lima kotak mengacu pada Pilpres dan Pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota). Pemilu Serentak ini tidak didasari oleh pembedaan antara pemilu nasional dan pemilu lokal.
Pemilu lokal selalu digambarkan hanya sebagai Pilkada. Tak menggambarkan sebuah pemerintahan daerah yang terdiri atas kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) dengan DPRD (provinsi dan kabupaten/kota).
Ketika mengevaluasi dan mencoba merumuskan kembali mekanisme Pemilu serentak untuk 2024. Tampak dipersidangan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi (Baleg) DPR, wakil rakyat tak mendasari pemilu serentak menyelaraskan dengan sistem pemerintahan.
Mereka terlihat jelas belum menyepakati adanya hubungan selaras antara pemerintahan nasional dengan pemerintahan lokal. Maksudnya bahwa Pemilu Nasional akan terdiri atas Pilpres dan Pemilu Legislatif dari lembaga DPR dan DPD, ini menunjukkan surat suara akan lebih sedikit dibandingkan dengan Pemilu 2019 lalu.
Baca juga: Pragmatisme Politik
Sedangkan pemilu lokal akan menyerentakkan antara pemilu legislatif (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dengan Pilkada (eksekutif daerah Gubernur, Bupati, Walikota).
Asumsi model baru ini adalah jika pemerintahan hasil pemilu serentak nasional memiliki kinerja baik, maka peta politik hasil pemilu serentak lokal kemungkinan besar sama, sehingga menghasilkan sinergi pemerintahan nasional dan lokal.
Di sisi lain, isu-isu politik lokal akan terangkat ke level nasional, di samping akan adanya evaluasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan pusat, serta semakin besarnya peluang elite politik lokal yang berhasil untuk bersaing menjadi elite politik di tingkat nasional, (Syamsuddin Haris, 2015).
Tawaran model baru ini diharapkan selain mengevaluasi dan mengatasi kerumitan, juga untuk menyelaraskan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah lokal. Namun sangat disayangkan, model ini sepertinya akan memperoleh penolakan masif oleh Wakil Rakyat di Senayan.
Jelas terdengar dengan gamblang, argumentasi untuk menolak, lebih didasari oleh kekuasaan semata. Wakil rakyat yang duduk di DPR, khawatir tidak akan terpilih kembali, karena keterpilihan mereka lebih disebabkan atas kerjasama dengan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten.
Pernyataan itu sebenarnya membuka tabir, wajar jika selama ini bahwa anggota DPR memang tak memahami persoalan konstituennya di tingkat daerah pemilihannya. Ini menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang yang populer di tingkat masyarakat daerahnya, keterpilihannnya terjadi karena kerjasama dengan anggota DPRD tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Hadirkan Banyak Calon Selaras dengan Multipartai
Sejak Pemilu 2014 lalu, meski Indonesia menganut sistem multipartai. Tetapi penetapan pasangan calon selalu mengerucut atas dua pasangan calon. Alasan yang menyertai, agar efisien tidak terjadi pemilihan presiden putaran kedua dan dianggap akan memperkokoh bangunan koalisi.
Wakil rakyat tentu saja menolak jika angka presidential threshold dinihilkan, dengan alasan untuk memperkokoh bangunan koalisi dan kokohnya koalisi dianggap akan menciptakan efektivitas dari pemerintah.
Pada dasarnya perilaku partai politik yang pragmatis membuat upaya kokohnya bangunan koalisi tak pernah terjadi. Sehingga berapa pasangan calon dan/atau jika terjadinya Pilpres dua putaran, tentu saja tak akan memengaruhi kokohnya bangunan koalisi.
Baca juga: Hilangnya Esensi Demokrasi
Bahkan, Pemilu 2019 ini menunjukkan dengan jelas bahwa Indonesia mengalami kemunduran berdemokrasi. Ketika terjadinya pasangan calon yang awalnya berkompetisi, malah ikut bergabung dalam koalisi pemerintahan yang terpilih.
Alasan penolakan dari wakil rakyat di Senayan, sepertinya akan lebih dikeraskan volumenya oleh partai besar. Ada pesan yang tersurat dari partai besar, mereka khawatir dengan menihilkan ambang batas pencalonan presiden akan berimbas pada kesempatan untuk mengajukan calon tak populer mengecil dan kesempatan memenangkan Pilpres juga turut mengecil.
Dengan membuka iklim kompetisi bagi partai-partai di Parlemen untuk mengajukan calon presiden, sebenarnya malah dapat meningkatkan kualitas partai.
Partai-partai dapat menunjukkan kualitas dari calon yang diajukan dan memastikan ‘mesin’ partai dapat bekerja dengan baik dan maksimal dalam memenangkan calon yang diajukan. Sebab, hanya calon yang populer dan memperoleh simpatik besar masyarakat yang akan dapat terpilih.
Dengan iklim kompetisi yang lebih terbuka, dapat menghadirkan semangat masyarakat dalam memilih pasangan calon presiden. Sebab, pemilih mengalami titik jenuh disebabkan dua kali pemilu tak adanya pasangan calon alternatif, ditambah dengan kelakukan pragmatis partai di Pemilu 2019 lalu, jika ini dibiarkan akan menyebabkan demokrasi di Indonesia semakin menjauhkan rakyat sebagai pemegang kuasa untuk antusias dalam memilih pemimpin.
Dengan iklim kompetisi yang lebih terbuka juga akan berdampak besar terhadap coattail effect, partai-partai yang dipilih dalam Pilpres cenderung dipilih juga oleh pemilih dalam Pemilu Legislatif yang diserentakkan tersebut.
Jika Pemilu 2019 lalu, coattail effect dianggap tidak bekerja maksimal, disebabkan partai-partai yang berkoalisi tidak benar-benar serius untuk mensukseskan kemenangan pasangan calon yang diusungnya.
Karena, partai-partai politik yang tidak mengajukan calon presiden, hanya menjadi mitra koalisi, mengkhawatirkan kesuksesan pasangan calon tersebut untuk menang, ternyata malah tak menghasilkan kenaikan perolehan suara partai tersebut.
Tentu saja akan berbeda, jika iklim kompetisi dibuka bagi partai-partai di parlemen untuk mengajukan calon presiden, kemungkinan besar coattail effect akan tercipta penuh seiring dengan kerja maksimal dari partai-partai untuk mewujudkan kemenangan pasangan yang dicalonkan juga meningkatkan perolehan suara dan kursi untuk partainya. (*)







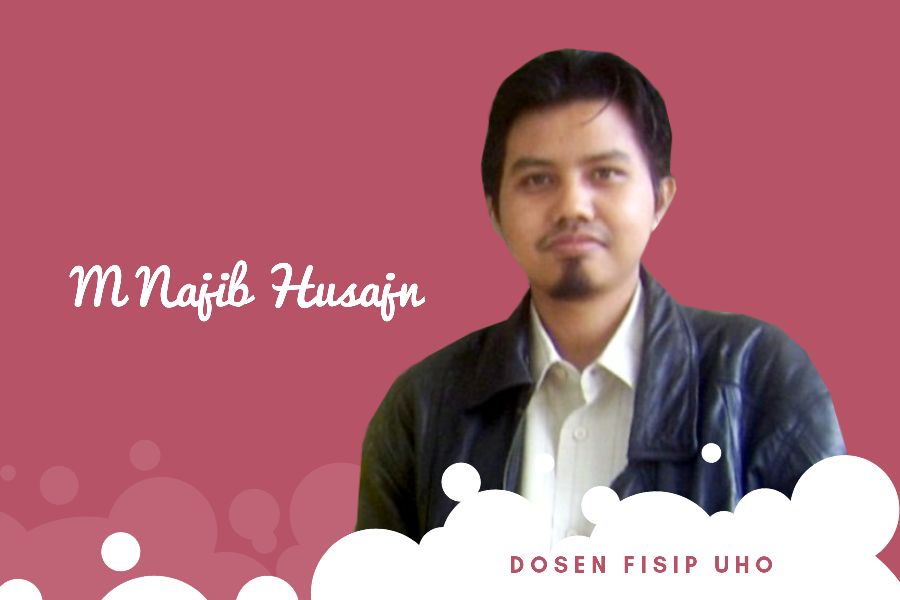







_(52).webp)


